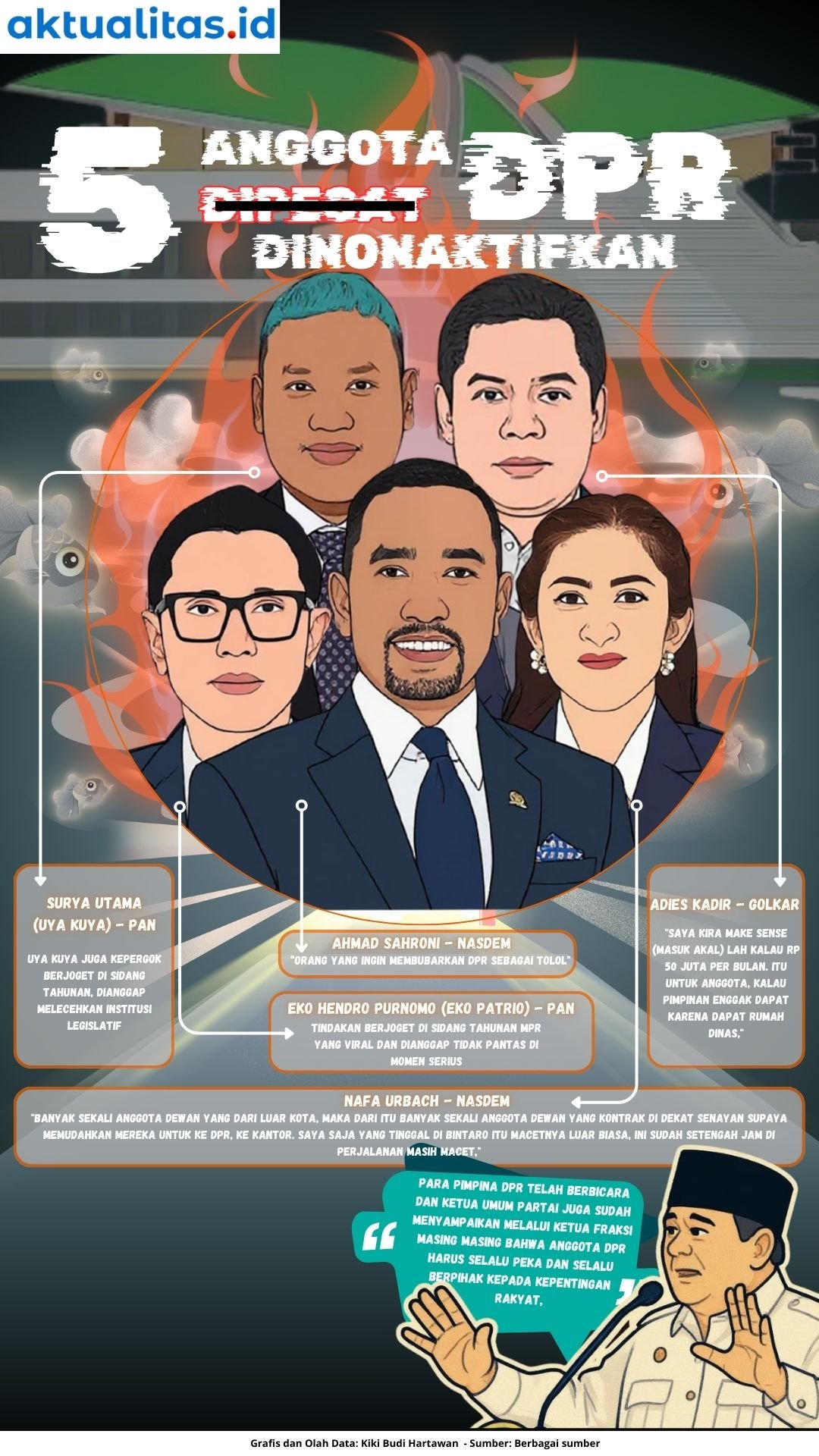POLITIK
Biaya Politik Pilkada Langsung Mencekik, Pengamat: Jadi Akar Korupsi Kepala Daerah

AKTUALITAS.ID – Sistem Pilkada langsung yang diterapkan sejak 2005 kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai mekanisme tersebut menciptakan beban biaya politik yang sangat tinggi bagi para kandidat kepala daerah.
Menurut Yusak, ongkos politik sudah membengkak sejak tahap pencalonan di partai politik hingga praktik politik uang di lapangan.
“Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kandidat seringkali memilih cara instan dengan politik uang karena keterbatasan waktu kampanye untuk menjangkau wilayah yang luas,” ujar Yusak, Minggu (15/2/2026).
Yusak menjelaskan, beban besar sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Untuk mendapatkan dukungan satu partai saja, kandidat disebut harus menyiapkan dana ratusan juta rupiah.
“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara biasa. Makanya muncul politik uang,” jelasnya.
Data dari Indonesia Political Review (IPR) memperkuat hal tersebut. Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebut anggaran negara untuk Pilkada langsung 2024 mencapai Rp38,2 triliun.
“Jika melalui DPRD, banyak proses yang terpangkas sehingga anggaran menjadi jauh lebih efisien. Namun, kita tetap harus waspada agar tidak mundur ke pola elitis yang rawan transaksi di tingkat legislatif,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai mahalnya ongkos Pilkada langsung menjadi salah satu pemicu korupsi kepala daerah.
“Masalahnya adalah ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu adalah salah satu akar korupsi di daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT),” tegas Dedi.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa pemilihan melalui DPRD bersifat anti-demokrasi. Menurutnya, konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan dilakukan secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan pemilihan langsung oleh rakyat.
“Anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Mandat publik sudah ada di parlemen daerah untuk mengambil keputusan strategis,” jelasnya.
Selain faktor ekonomi, Pilkada langsung juga dinilai memicu polarisasi sosial di tingkat akar rumput. Dedi menilai mekanisme perwakilan berpotensi meredam ketegangan politik identitas yang sering muncul saat kontestasi langsung.
“Dalam sistem perwakilan, konflik politik kembali ke ruang elite, tidak ditarik ke dapur warga. Ini lebih sesuai dengan esensi demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah dan perwakilan,” pungkasnya.
Wacana evaluasi sistem Pilkada langsung pun kembali mengemuka, seiring tingginya biaya politik, beban anggaran negara, serta risiko korupsi kepala daerah yang terus menjadi perhatian publik. (Bowo/Mun)